INVERTING AMPLIFIER
1. Pendahuluan (kembali)
Dalam
dunia elektronika analog, penguat operasional atau Op-Amp (Operational
Amplifier) merupakan salah satu komponen aktif yang sangat serbaguna dan banyak
digunakan. Op-Amp memiliki penguatan tegangan yang sangat tinggi dan dapat
digunakan dalam berbagai konfigurasi rangkaian, salah satunya adalah Inverting
Amplifier.
Inverting
Amplifier adalah konfigurasi dasar dari Op-Amp di mana sinyal input diberikan
ke terminal inverting (-) dan output akan menghasilkan sinyal yang berlawanan
fasa (180°) terhadap input, serta diperkuat sesuai dengan rasio resistor yang
digunakan. Konfigurasi ini penting karena memberikan kemampuan penguatan dengan
kestabilan tinggi, linearitas yang baik, dan respons frekuensi yang luas.
Penggunaan
inverting amplifier banyak ditemukan dalam sistem pengolahan sinyal, sensor,
kontrol industri, dan berbagai aplikasi elektronika lainnya. Oleh karena itu,
pemahaman yang baik terhadap prinsip kerja dan karakteristik inverting
amplifier sangat penting bagi mahasiswa teknik elektro, khususnya dalam
memahami dasar perancangan sistem analog.
2. Tujuan (kembali)
1) Memahami prinsip kerja Inverting
Amplifier menggunakan Op-Amp 741.
2) Menganalisis penguatan sinyal lemah dari berbagai jenis sensor menggunakan konfigurasi inverting amplifier.
3) Menerapkan rangkaian inverting amplifier untuk memperkuat sinyal dari sensor gas, sensor thermocouple, dan sensor flame.
3.
Alat dan Bahan (kembali)
A) ALAT
1) OSILOSKOP
2) MULTIMETER
B) BAHAN
1) RESISTOR
2) DIODA
ZENER
3) GROUND
4) SENSOR
GAS
5) SENSOR
THERMOCOUPLE
6) SENSOR
API
7) OPA-AMP

4.
Dasar Teori (kembali)
A) Op-Amp (Operational
Amplifier)
Penguat operasional (Operational Amplifier) atau yang
biasa disebut dengan op-amp, merupakan penguat elektronika yang banyak
digunakan untuk membuat rangkaian detektor, komparator, penguat audio, video,
pembangkit sinyal, multivibrator, filter, ADC, DAC, rangkaian penggerak dan
berbagai macam rangkaian analog lainnya. Op-amp pada umumnya tersedia dalam
bentuk rangkaian terpadu yang memiliki karakteristik mendekati karakteristik
penguat operasional ideal tanpa perlu memperhatikan apa yang terdapat di
dalamnya. Ada tiga karakteristik utama op-amp ideal, yaitu;
1) Gain
sangat besar (AOL >>).
Penguatan
open loop adalah sangat besar karena feedback-nya tidak ada atau RF = tak terhingga.
2) Impedansi
input sangat besar (Zi >>).
Impedansi
input adalah sangat besar sehingga arus input ke rangkaian dalam op-amp sangat
kecil sehingga tegangan input sepenuhnya dapat dikuatkan.
3) Impedansi output sangat kecil (Zo <<).
Impedansi output adalah sangat kecil sehingga tegangan output stabil karena tahanan beban lebih besar yang diparalelkan dengan Zo <<.
Adapun simbol op-amp adalah seperti pada gambar 1
 |
| Gambar 1 |
dimana,
V1 adalah
tegangan masukan dari kaki non inverting
V2 adalah
tegangan masukan dari kaki inverting
Vo adalah tegangan keluaran
sehingga
Adapun tegangan output maksimum
yang dapat dihasilkan adalah :
dibawah tegangan sumber +-Vs =
+-Vsat
Tegangan output maksimum secara praktis dihasilkan sekitar 2 Volt dibawah
tegangan sumber ±Vs dan disebut juga sebesar tegangan saturasi ±Vsat
. Gambar 65 memperlihatkan kurva karakteristik hubungan Vi terhadap Vo untuk
rangkaian op-amp dengan tegangan input dihubungkan ke kaki input non inverting
(+) dan tegangan 0 Volt (di ground) ke kaki input inverting (-). Sesuai dengan
nama input op-amp yaitu apabila input dimasukkan ke kaki non inverting (+) yang
artinya tidak membalik maka tegangan output yang dihasilkan adalah sefasa
dengan tegangan input. Seperti terlihat pada gambar 112 yaitu saat input Vi
bertegangan positif maka output yang dihasilkan juga bertegangan positif dan
sebaliknya
Rangkaian inverting amplifier adalah seperti gambar 113 dimana sesuai dengan
namanya yaitu dengan input dimasukkan ke kaki inverting (pembalik) sehingga
output akan dibalik atau beda fasa sebesar 180 derajat
Untuk mencari turunan penguatan tegangan ACL maka rangkaian dimisalkan dahulu dengan input dc positif, seperti gambar 114. Dalam analisa rangkaian amplifier disyaratkan op-amp bekerja ideal sehingga tegangan differensial (selisih tegangan di kaki non inverting terhadap tegangan di kaki inverting) Ed = 0, artinya VA (tegangan di titik A) = 0 sehingga arus yang melewati Ri sama dengan arus yang melewati Rf karena arus yang masuk ke kaki inverting sangat kecil karena sifat op-amp dimana impendasi (Zi) inputnya sangat besar. Adapun rangkaian pengganti untuk menghitung arus I adalah seperti gambar 2
 |
| Gambar 2 |
Gambar
10 Rangkaian inverting amplifier dengan input dc positif
Dari rangkaian
gambar 10 dengan Ed = 0 maka VA = 0 sehingga rangkaian dapat disederhanakan
menjadi seperti gambar 115 untuk mencari arus
Dengan I = V / R maka dapat
dicari ACL untuk gambar 115, yaitu;
Bentuk
gelombang tegangan output VO adalah seperti pada gambar 116 dan karakteristik
I-O seperti pada gambar 117
B) Resistor
Resistor merupakan komponen penting dan sering dijumpai
dalam sirkuit Elektronik. Boleh dikatakan hampir setiap sirkuit Elektronik
pasti ada Resistor. Tetapi banyak diantara kita yang bekerja di perusahaan
perakitan Elektronik maupun yang menggunakan peralatan Elektronik tersebut
tidak mengetahui cara membaca kode warna ataupun kode angka yang ada ditubuh
Resistor itu sendiri.
Seperti yang dikatakan sebelumnya,
nilai Resistor yang berbentuk Axial adalah diwakili oleh Warna-warna yang
terdapat di tubuh (body) Resistor itu sendiri dalam bentuk Gelang. Umumnya
terdapat 4 Gelang di tubuh Resistor, tetapi ada juga yang 5 Gelang.
Gelang warna Emas dan Perak
biasanya terletak agak jauh dari gelang warna lainnya sebagai tanda gelang
terakhir. Gelang Terakhirnya ini juga merupakan nilai toleransi pada nilai
Resistor yang bersangkutan.
Tabel dibawah ini adalah
warna-warna yang terdapat di Tubuh Resistor :
Perhitungan untuk Resistor dengan 4 Gelang warna :
Cara menghitung nilai resistor 4
gelang:
1)
Masukkan
angka langsung dari kode warna Gelang ke-1 (pertama)
2)
Masukkan
angka langsung dari kode warna Gelang ke-2
3)
Masukkan
Jumlah nol dari kode warna Gelang ke-3 atau pangkatkan angka tersebut dengan 10
(10n)
4) Merupakan Toleransi dari nilai Resistor tersebut
Contoh pembacaan 4 gelang warna:
Gelang ke 1 : Coklat = 1
Gelang ke 2 : Hitam = 0
Gelang ke 3 : Merah = 2 nol dibelakang
angka gelang ke-2; atau kalikan 100
Gelang ke 4 : Perak = Toleransi 5%
Maka nilai Resistor tersebut adalah
10 * 100 = 1.000 Ohm atau 1Kohm dengan toleransi 5%.
Perhitungan untuk Resistor dengan 5
Gelang warna :
Cara Menghitung Nilai Resistor 5
Gelang Warna:
1)
Masukkan
angka langsung dari kode warna Gelang ke-1 (pertama)
2)
Masukkan
angka langsung dari kode warna Gelang ke-2
3)
Masukkan
angka langsung dari kode warna Gelang ke-3
4)
Masukkan
Jumlah nol dari kode warna Gelang ke-4 atau pangkatkan angka tersebut dengan 10
(10n)
5)
Merupakan
Toleransi dari nilai Resistor tersebut
Contoh pembacaan 5 gelang warna:
Gelang ke 1 : Merah = 2
Gelang ke 2 : Merah = 2
Gelang ke 3 : Hitam = 0
Gelang ke 4 : Hitam = 0 nol
dibelakang angka gelang ke-3; atau kalikan 0
Gelang ke 5 : Emas = Toleransi 5%
Maka nilai Resistor tersebut adalah
220 * 1 = 220 Ohm dengan toleransi 5%.
Contoh-contoh perhitungan lainnya :
Merah, Merah,
Merah, Emas → 22 * 10² = 2.200 Ohm atau 2,2 Kilo Ohm dengan 5% toleransi
Kuning, Ungu, Orange, Perak → 47 * 10³ = 47.000 Ohm atau 47 Kilo Ohm dengan 10%
toleransi
Cara menghitung Toleransi :
2.200 Ohm dengan Toleransi 5% =
2200 – 5% = 2.090
2200 + 5% = 2.310
ini artinya nilai Resistor tersebut
akan berkisar antara 2.090 Ohm ~ 2.310 Ohm
C) Osiloskop
adalah alat ukur elektronik yang
berfungsi untuk memproyeksikan frekuensi dan sinyal listrik dalam bentuk
grafik.
1)
Tombol/Sakelar
dan Indikator Osiloskop
2)
Tombol
Power ON/OFF
Tombol Power ON/OFF berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan Osiloskop
3)
Lampu
Indikator
Lampu Indikator berfungsi sebagai Indikasi Osiloskop dalam keadaan ON (lampu
Hidup) atau OFF (Lampu Mati)
4)
ROTATION
Rotation pada Osiloskop berfungsi untuk mengatur posisi tampilan garis pada
layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Untuk mengatur rotation ini,
biasanya harus menggunakan obeng untuk memutarnya.
5)
INTENSITY
Intensity digunakan untuk mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar
mudah dilihat.
6)
FOCUS
Focus digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur
7)
CAL
CAL digunakan untuk Kalibrasi tegangan peak to peak (VP-P) atau Tegangan puncak
ke puncak.
8)
POSITION
Posistion digunakan untuk mengatur posisi Vertikal (masing-masing
Saluran/Channel memiliki pengatur POSITION).
9)
INV
(INVERT)
Saat tombol INV ditekan, sinyal Input yang bersangkutan akan dibalikan.
10)
Sakelar
VOLT/DIV
Sakelar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter
(Volt/Div) pada layar Osiloskop. Umumnya, Osiloskop memiliki dua saluran (dual
channel) dengan dua Sakelar VOLT/DIV. Biasanya tersedia pilihan 0,01V/Div
hingga 20V/Div.
11)
VARIABLE
Fungsi Variable pada Osiloskop adalah untuk mengatur kepekaan (sensitivitas)
arah vertikal pada saluran atau Channel yang bersangkutan. Putaran Maksimum
Variable adalah CAL yang berfungsi untuk melakukan kalibrasi Tegangan 1 Volt
tepat pada 1cm di Layar Osiloskop.
12)
AC
– DC
Pilihan AC digunakan untuk mengukur sinyal AC, sinyal input yang mengandung DC
akan ditahan/diblokir oleh sebuah Kapasitor. Sedangkan pada pilihan posisi DC
maka Input Terminal akan terhubung langsung dengan Penguat yang ada di dalam
Osiloskop dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar Osiloskop.
13)
GND
Jika tombol GND diaktifkan, maka Terminal INPUT akan terbuka, Input yang
bersumber dari penguatan Internal Osiloskop akan ditanahkan (Grounded).
14)
VERTICAL
INPUT CH-1
Sebagai VERTICAL INPUT untuk Saluran 1 (Channel 1)
15)
VERTICAL
INPUT CH-2
Sebagai VERTICAL INPUT untuk Saluran 2 (Channel 2)
16)
Sakelar
MODE
Sakelar MODE pada umumnya terdiri dari 4 pilihan yaitu CH1, CH2, DUAL dan ADD.
CH1=Untuk tampilan bentuk gelombang Saluran 1 (Channel 1).
CH2=Untuk tampilan bentuk gelombang Saluran 2 (Channel 2).
DUAL = Untuk menampilkan bentuk gelombang Saluran 1 (CH1) dan Saluran 2 (CH2)
secara bersamaan.
ADD = Untuk menjumlahkan kedua masukan saluran/saluran secara aljabar. Hasil
penjumlahannya akan menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar.
17)
x10
MAG
Untuk pembesaran (Magnification) frekuensi hingga 10 kali lipat.
18)
POSITION
Untuk penyetelan tampilan kiri-kanan pada layar.
19)
XY
Pada fungsi XY ini digunakan, Input Saluran 1 akan menjadi Axis X dan Input
Saluran 2 akan menjadi Axis Y.
20)
Sakelar
TIME/DIV
Sakelar TIME/DIV digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode
atau per satu kotak cm pada layar Osiloskop.
21)
Tombol
CAL (TIME/DIV)
ini berfungsi untuk kalibrasi TIME/DIV
22)
VARIABLE
Fungsi Variable pada bagian Horizontal adalah untuk mengatur kepekaan
(sensitivitas) TIME/DIV.
23)
GND
GND merupakan Konektor yang dihubungkan ke Ground (Tanah).
24)
Tombol
CHOP dan ALT
CHOP adalah menggunakan potongan dari saluran 1 dan saluran 2.
ALT atau Alternate adalah menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara
bergantian.
25)
HOLD
OFF
HOLD OFF untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop.
26)
LEVEL
LEVEL atau TRIGGER LEVEL digunakan untuk mengatur gambar yang diperoleh menjadi
diam atau tidak bergerak.
27)
Tombol
NORM dan AUTO
28)
Tombol
LOCK
29)
Sakelar
COUPLING
Menunjukan hubungan dengan sinyal searah (DC) atau bolak balik (AC).
30)
Sakelar
SOURCE
Penyesuai pemilihan sinyal.
31)
TRIGGER
ALT
32)
SLOPE
33)
EXT
Trigger yang dikendalikan dari rangkaian di luar Osiloskop.
D) Grounding
adalah suatu sistem penghubung antara bagian
dari rangkaian listrik atau perangkat elektronik ke tanah (ground) dengan
tujuan untuk menjaga keselamatan serta kestabilan sistem. Ground berfungsi
sebagai titik referensi tegangan nol dan sebagai jalur pelepasan arus berlebih
atau gangguan, seperti lonjakan tegangan, petir, atau gangguan elektromagnetik.
Dalam
konteks rangkaian elektronika, grounding membantu mencegah noise dan
interferensi dengan memberikan jalur kembali arus gangguan ke tanah. Sistem
ground yang baik sangat penting agar sinyal tidak terganggu dan peralatan dapat
bekerja dengan optimal. Ada beberapa jenis grounding, seperti grounding
fungsional (fungsi kerja sistem), grounding pelindung (safety), dan grounding
sinyal (untuk kestabilan sinyal).
E) Thermocouple
Termokopel atau penulisan bahasa
Inggrisnya Thermocouple adalah komponen berupa sensor suhu
yang dapat digunakan untuk mengukur temperatur dengan memanfaatkan efek thermo-electric yang dihasilkan dari dua
jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya. Kurang lebih seperti
itu pengertian thermocouple.
Efek Thermoelektrik yang diterapkan
untuk membuat Termokopel ini pertama dicetuskan Tahun 1821 oleh seorang
fisikawan Estonia bernama Thomas Johann Seebeck. Efek tersebut pun dinamakan
Efek Seebeck, yaitu Perbedaan Tegangan listrik yang dihasilkan ketika dua logam
konduktor diberi perbedaan panas secara gradient.
Termokopel ini cukup populer
digunakan. Fungsi termokopel yang mendeteksi suhu membuatnya dibutuhkan di
berbagai rangkaian ataupun peralatan listrik. Diantara kelebihan thermocouple
yang membuatnya sangat diminati adalah kecepatan respon komponen ini terhadap
perubahan suhu yang cukup tinggi dan juga memiliki rentang suhu operasional
yang luas yaitu dari -200˚C hingga 2000˚C.
Prinsip kerja thermocouple
Thermocouple
bekerja berdasarkan prinsip efek Seebeck, yaitu fenomena di mana tegangan
listrik muncul ketika dua logam berbeda disambungkan pada dua titik dengan suhu
berbeda. Satu ujung disebut hot junction (sambungan panas) dan satu lagi
cold junction (sambungan referensi). Ketika suhu pada hot junction
meningkat, akan terjadi perbedaan potensial antara kedua logam, sehingga
menghasilkan tegangan listrik sebanding dengan perbedaan suhu.
Tegangan
kecil yang dihasilkan ini kemudian diukur dan dikonversi menjadi nilai suhu
menggunakan alat ukur atau rangkaian penguat seperti op-amp, karena
sinyal dari thermocouple umumnya sangat kecil (dalam milivolt). Thermocouple
banyak digunakan karena mampu mengukur suhu tinggi, respon cepat, dan bentuknya
sederhana.
Prinsip
Kerja Thermocouple
Prinsip
kerja thermocouple pada bedasarkan pada 3 hukum; Hukum Seebeck, Hukum Peltier,
dan Hukum Thomson.
·
Hukum
Seebeck
Hukum Seebeck menyatakan bahwa
ketika dua metal yang berlainan disatukan dalam dua ujungnya, maka ia akan
menimbulkan gaya electromotive (emf). Gaya yang dihasilkan akan berbeda antara
metal jenis yang satu dengan jenis lainnya.
·
Hukum
Peltier
Hukum Peltier menyatakan bahwa
ketika dua metal yang berlainan jenisnya disatukan, ia akan menghasilkan gaya
EMF tergantung dari suhu yang dialami oleh kedua ujung yang disatukan.
· Hukum ThompsonHukum
Thompson menyebutkan bahwa ketika dua metal yang berlainan jenisnya disatukan maka ia akan menghasilkan gaya EMF tergantung dari gradien suhu dan panjang konduktor dari dua metal tersebut.
Dari ketiga hukum tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip kerja
thermocouple adalah dengan menyatukan dua metal (kabel) yang memiliki material
pembentuk yang berbeda dimana ketika metal ini disatukan di salah satu ujung,
ia akan membangkitkan EMF yang dapat disesuaikan dengan standar tergantung
dengan jenis metal, suhu yang diterimanya serta panjang metal dari ujung sensor
ke alat ukurnya.
Jenis-jenis
Thermocouple dan Range Ukurnya
Ada banyak jenis thermocouple. Saya
hanya akan menyebutkan 3 yang paling umum digunakan.
· · Type J
Thermocouple tipe J adalah thermocouple
yang paling banyak digunakan di industri petrokimia. Hal ini disebabkan range
ukurnya yang pendek dan paling umum yakni di -210 degC hingga 760 degC.
Thermocouple type J sangat cocok digunakan untuk mengukur suhu air, suhu udara
normal, suhu atmosfer, suhu low temperature steam, suhu condensate dan
sebagainya. Ciri umum kabel thermocouple type J adalah kabel positif berwarna
putih dan kabel negatifnya berwarna merah. Bahan pembentuk kabel thermocouple
type J adalah Fe (+) dan Cu-Ni (-). Meski begitu, kabel thermocouple type J
tidak terlalu bagus untuk mengukur suhu tinggi semacam high temperature steam
sebab daya tahan kabelnya tidak bagus jika digunakan untuk suhu tinggi.
·
Type
K
Thermocouple type K adalah
thermocouple lain yang banyak juga dipakai di industri petrokimia. Biasanya
thermocouple jenis ini dipakai untuk mengukur ruang bakar seperti di boiler,
reformer, super heater dan high temperature steam. Warna kabel thermocouple
type K pada umumnya berwarna kuning untuk kabel positif dan merah untuk kabel
negatif dengan range ukur -260 degC sampai 1200 degC. Bahan kabel thermocouple
adalah Ni-Cr (+) dan Ni-Al (-)
·
Type
T
Thermocouple type T biasanya
digunakan untuk mengukur suhu yang sangat dingin. Bahan pembuatnya adalah Cu
(+) dan Cu-Ni (-). Range ukurnya berkisar -270 degC hingga 370 degC. Warna
kabel type T adalah biru - merah.
Untuk
ringkasan tabel referensi milivolt temperature dapat dilihat di grafik berikut
ini.
Ringkasan
batas ukur thermocouple dapat dilihat di tabel berikut in
Berikut ringkasan standar kode
warna kabel thermocouple
F) Flame Sensor
Salah satu detektor yang
memiliki fungsi terpenting adalah detektor api atau yang biasa disebut dengan
Flame Detector yang mampu mengaktifkan alarm bila mendeteksi adanya percikan
api yang berisiko menyebabkan bencana kebakaran. Namun, saat memilih Flame
Detector, pengguna diharuskan telah benar-benar paham atas prinsip dari alat
detektor tersebut dan meninjaunya demi mendapatkan Flame Detector yang sesuai
dengan aktivitas di dalam lokasi dan tingkat kebutuhannya, serta bagaimana
konsekuensi risiko yang mungkin terjadi.
Prinsip Flame Detektor
tersebut menggunakan metode optik yang bekerja seperti UV (ultraviolet) dan IR
(infrared), pencitraan visual api, serta spektroskopi yang berfungsi untuk
mengidentifikasi percikan api atau flame. Reaksi intens bahan yang memicu kebakarfan
dapat ditandai dari UV, terlihatnya emisi karbondioksida, dan radiasi dari
infrared. Flame Detector juga mampu membedakan antara False Alarm atau
peringatan palsu dengan api kebakaran sungguhan melalui komponen sistem yang
dirancang dengan fungsi mendeteksi adanya penyerapan cahaya yang terjadi pada
gelombang tertentu.
Tingkat potensi risiko
kebakaran dari setiap jenis bahan semakin meluas mengingat semakin canggihnya
teknologi penginderaan api atau teknologi Flame Sensing. Pada umumnya bahan
bakar industri yang tergolong mudah terbakar antara lain: bensin, hidrogen, belerang,
alkohol, LNG/LPG, minyak tanah, kertas, disel, kayu, jet bahan bakar, tekstil,
ethylene, dan pelarut.
G) Sensor Gas MQ2
Sensor MQ-2 adalah sensor
yang digunakann untuk mendeteksi konsentrasi gas yang mudah terbakar di udara
serta asap dan output membaca sebagai tegangan analog. Sensor gas asap MQ-2
dapat langsung diatur sensitifitasnya dengan memutar trimpotnya. Sensor ini
biasa digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas baik di rumah maupun di
industri. Gas yang dapat dideteksi diantaranya : LPG, i-butane, propane,
methane , alcohol, Hydrogen, smoke. Sensor MQ2 memiliki symbol seperti
gambar di bawah ini :
 |
| Gambar Simbol Sensor MQ2 |
 |
| Grafik Sensifitas Sensor |
H) Diode Zener
Dioda
Zener adalah jenis dioda khusus yang dirancang untuk beroperasi dalam kondisi bias
balik (reverse bias), yaitu ketika tegangan diberikan dari katoda ke anoda.
Berbeda dengan dioda biasa yang rusak jika diberikan tegangan balik melebihi
batasnya, dioda Zener tetap aman dan menjaga tegangan tetap stabil pada nilai
tertentu yang disebut tegangan Zener.
Ketika
tegangan balik mencapai nilai tegangan Zener, dioda mulai menghantar arus
secara stabil tanpa menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, dioda Zener banyak
digunakan dalam rangkaian regulator tegangan untuk memberikan tegangan
referensi tetap, serta sebagai pelindung terhadap lonjakan tegangan.
Karakteristik
penting dari dioda Zener adalah kemampuannya untuk menjaga tegangan tetap
konstan meskipun arus berubah-ubah, selama berada dalam batas spesifikasinya.
Kode diode ZeneR
Dioda
Zener dapat dibedakan dari dioda biasa dengan kode dan tegangan tembus yang
tercetak di atasnya. Kode dioda Zener umumnya dimulai dengan huruf BZX... atau BZY...
Tegangan
tembusnya dicetak dengan huruf V sebagai pengganti titik desimal, sebagai
contoh kode dioda zener 4V7 artinya memiliki tegangan 4.7 V. Tegangan minimum
yang tersedia adalah 2.7V.
Untuk
lebih memahami lagi, berikut contoh cara membaca kode dioda zener yang bisa
Anda pelajari:
·
Kode
5.1 artinya tegangan = 5.1 Volt
· Kode 5V1 artinya tegangan = 5.1
Volt
· Kode 12 artinya tegangan = 12 Volt
·
Kode
12V artinya tegangan = 12 Volt
Selanjutnya bisa Anda simak daftar tabel kode dioda zener yang bisa Anda jadikan referensi:
Karakteristik
Dioda Zener I-V
Dioda zener digunakan dalam “reverse bias” atau membalikkan modus pemecahan,
yaitu dioda anoda terhubung ke catu negatif. Dari kurva karakteristik I-V di
atas, kita dapat melihat bahwa dioda zener memiliki daerah dalam karakteristik
reverse bias hampir tegangan negatif konstan terlepas dari nilai arus yang
mengalir melalui dioda dan tetap hampir konstan bahkan dengan perubahan besar
dalam arus sebagai selama arus dioda zener tetap antara arus breakdown IZ(min) dan
tingkat arus maksimum IZ(max).
Kemampuan untuk mengontrol itu sendiri dapat digunakan untuk efek besar untuk
mengatur atau menstabilkan sumber tegangan terhadap variasi supply atau beban.
Fakta bahwa tegangan melintasi dioda di daerah breakdown hampir konstan
ternyata menjadi karakteristik penting dari dioda zener karena dapat digunakan
dalam jenis aplikasi pengatur tegangan paling sederhana.
Fungsi Regulator adalah untuk memberikan tegangan output konstan ke beban
yang terhubung secara paralel dengan itu terlepas dari riak dalam tegangan
supply atau variasi dalam arus beban dan dioda zener akan terus mengatur
tegangan hingga arus dioda turun di bawah nilai IZ(min) minimum
di wilayah reverse breakdown.
5. Prinsip Kerja [kembali]
Rangkaian proteksi asap dan kebakaran ini bekerja diawali
oleh aktifnya tombol sentuh yang mengaktifkan sistem melalui rangkaian
inverting amplifier. Setelah sistem aktif, sensor gas MQ-7 akan mendeteksi
keberadaan asap. Jika terdeteksi, buzzer dan LED indikator akan menyala sebagai
tanda peringatan. Sistem dilengkapi dengan mekanisme latch sehingga tetap aktif
meskipun tombol dilepas. Selain itu, flame sensor akan mendeteksi keberadaan
api dan memicu buzzer serta motor sebagai respon kebakaran. Relay digunakan
untuk mengontrol beban eksternal saat alarm aktif sebagai bagian dari sistem
proteksi otomatis.
6.
Problem [kembali]
1) Transistor tidak aktif
meskipun sensor dan op-amp sudah menghasilkan output HIGH.
Kemungkinan Penyebab dan Solusi: Tegangan output op-amp terlalu
kecil (< 0,7 V) sehingga tidak cukup mengaktifkan basis transistor → Solusi:
Gunakan op-amp dengan output rail-to-rail atau tambahkan buffer. Basis resistor terlalu besar → Solusi:
Kurangi nilai resistor basis untuk memastikan arus basis cukup besar agar
transistor aktif.
2) Sensor Tidak Memberikan Output
Sesuai
Masalah:
Sensor api selalu output 0 V meskipun ada api.
Kemungkinan Penyebab dan Solusi: Sensor rusak atau tidak mendapatkan
tegangan catu → Solusi: Periksa tegangan VCC dan ground sensor. Sensor tidak terkalibrasi dengan
benar → Solusi: Sesuaikan sensitivitas sensor dengan potensiometer (jika ada).
3) Relay Tidak Aktif saat Output Aktif
Masalah:
Op-amp HIGH, tapi relay tidak aktif.
Pemeriksaan: Cek transistor driver apakah sudah
aktif → Ukur tegangan basis-emitor. Cek kondisi relay → Mungkin
kumparan putus.
7.
Soal Latihan [kembali]
Sebuah
sensor gas MQ-2 menghasilkan tegangan output sebesar 2,5 V saat mendeteksi
kebocoran gas. Tegangan referensi pada input pembanding diatur sebesar 2,0 V.
Jawaban:
Karena tegangan dari sensor (2,5 V) lebih tinggi dari tegangan
referensi (2,0 V), maka output op-amp pembanding menjadi HIGH (aktif). Sinyal
ini akan mengaktifkan transistor sebagai saklar, yang kemudian mengaktifkan
relay untuk memutus aliran listrik pada boiler, serta memberi sinyal ke buzzer
atau indikator untuk peringatan dini kebocoran gas.
Sensor api mendeteksi adanya nyala api dengan output 0,5 V. Suatu waktu, output
sensor turun menjadi 0,1 V, sementara tegangan referensi pembanding adalah 0,3
V.
Jawaban:
Karena 0,1 V < 0,3 V, maka op-amp pembanding akan menghasilkan output HIGH sebagai sinyal bahwa tidak ada api. Sistem akan menganggap api padam secara tiba-tiba. Maka transistor akan aktif, relay memutus sistem pembakaran, dan buzzer akan menyala sebagai peringatan adanya gangguan api atau potensi kebakaran.
Jelaskan
bagaimana peran op-amp sebagai pembanding bekerja dalam sistem ini.
Jawaban:
Op-amp sebagai pembanding membandingkan sinyal dari sensor (input
inverting/non-inverting) dengan tegangan referensi. Jika tegangan sensor
melebihi referensi, maka output akan HIGH. Jika tidak, output akan LOW. Ini
berguna untuk membuat sistem otomatis dalam mendeteksi kondisi bahaya (seperti
gas atau api) berdasarkan tegangan batas (threshold).
8.
Percobaan [kembali]
Persiapan
Awal
1)
Buka
software Proteus dan buka file rangkaian "Aplikasi Proteksi Boiler"
yang telah dibuat.
2) Periksa
koneksi rangkaian untuk memastikan semua komponen telah terhubung dengan benar:
a.
Sensor
Gas (MQ-2)
b.
Sensor
Api (Flame Sensor)
c.
Op-Amp
sebagai penguat dan pembanding
d.
Transistor,
relay, buzzer, dan indikator LED
3)
Pastikan
sumber tegangan (VCC) telah disambungkan ke semua rangkaian (biasanya 5V atau
12V sesuai spesifikasi komponen).
4)
Simpan
proyek untuk menghindari kehilangan data jika terjadi kesalahan.
Pengujian Sensor
Gas (MQ-2)
5.
Jalankan
simulasi dengan mengklik tombol “Run Simulation” di Proteus.
6. Variasikan
tegangan keluaran dari sensor gas (MQ-2) secara manual (misal dengan
potensiometer atau pengaturan langsung tegangan).
7.
Perhatikan
respon rangkaian:
·
Jika
konsentrasi gas rendah → tegangan output MQ-2 < referensi → relay
tidak aktif, buzzer mati.
·
Jika
konsentrasi gas tinggi → tegangan output MQ-2 > referensi → Op-Amp
aktif, transistor mengalirkan arus, relay aktif → buzzer dan LED menyala.
8.
Catat
kondisi saat buzzer aktif sebagai indikasi sistem proteksi gas bekerja.
Pengujian Sensor
Api (Flame Sensor)
9. Atur
output flame sensor (bisa menggunakan sinyal tegangan input) agar
mensimulasikan keberadaan api (tegangan tinggi) dan tidak ada api (tegangan
rendah).
10. Saat
tegangan flame sensor tinggi (misalnya 5V) → sistem tidak aktif → relay
dan buzzer mati.
11.
Turunkan
tegangan flame sensor di bawah nilai referensi (misal < 1V) untuk
mensimulasikan kondisi kehilangan api.
12.
Perhatikan
perubahan pada output:
Jika tidak ada api → output pembanding
aktif → transistor ON → relay aktif → buzzer dan LED menyala.
13.
Catat
hasil respon sistem saat mendeteksi kehilangan api.
Pengujian Gabungan
(Kondisi Bahaya Ganda)
14.
Simulasikan
kondisi kebocoran gas dan kehilangan api secara bersamaan dengan menaikkan output MQ-2 dan menurunkan
output flame sensor secara bersamaan.
15.
Amati
apakah kedua rangkaian proteksi (gas dan api) aktif secara bersamaan.
16.
Pastikan
kedua buzzer dan relay menyala untuk memberi peringatan bahaya ganda.
17. Setelah itu, kembalikan tegangan output sensor ke kondisi normal (tanpa gas dan api t erdeteksi normal), lalu pastikan sistem mati kembali (relay off, buzzer mati).
9. Download File [kembali]
Rangkaian Simulasi link disini
Download Datasheets resistor klik
disini
Download Datasheets Inverting
Amplifier klik
disini
Download Datasheets
Amperemeter klik
disini
Download Datasheets Voltmeter klik
disini
Download Datasheets Opamp klik
disini
Download Datasheets
Osilloscop klik
disini
Download Datasheets Rilay klik
disini
Donload Datasheet Flame
sensor klik
disini
Download library Sensor Flame klik
disini




















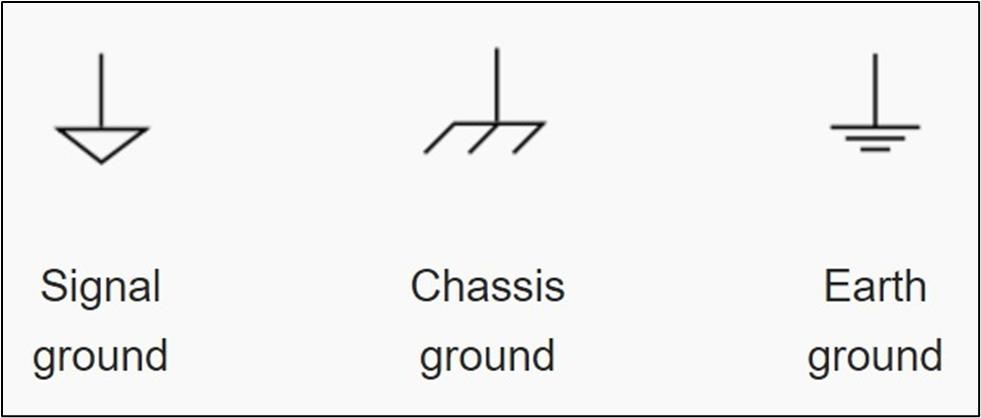




















Komentar
Posting Komentar